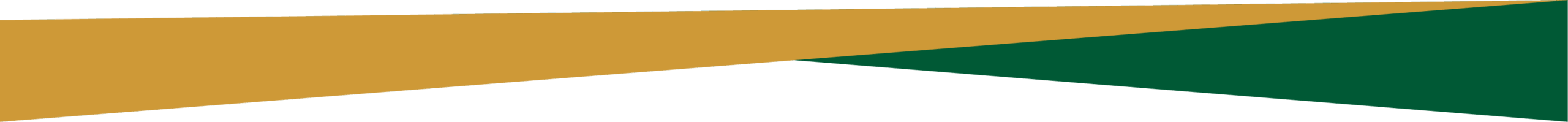HUMANIORA – (18/2/2026) Ramadhan sering dipahami sebagai bulan ibadah dalam pengertian ritual: puasa, tarawih, tilawah, dan zakat. Namun, bila dilihat melalui lensa humaniora, Ramadhan bukan sekadar momentum spiritual individual, melainkan peristiwa kebudayaan, etika, dan kemanusiaan yang menghadirkan transformasi sosial. Humaniora—yang mencakup kajian tentang manusia, makna, nilai, bahasa, sejarah, dan budaya—mengajak kita membaca Ramadhan sebagai pengalaman eksistensial: bagaimana manusia memaknai lapar, waktu, relasi sosial, dan Tuhan.
Baca juga:
- Dari Kemanusiaan hingga Krisis Global, Humaniora Tetap Relevan
- Tarhib Ramadan 2026: Momentum Transformasi Spiritual dan Etos Kerja di Fakultas Humaniora
Dalam perspektif ini, Ramadhan bukan hanya kewajiban syariat, tetapi juga ruang refleksi tentang siapa manusia dan untuk apa ia hidup.
Ramadhan sebagai Narasi Kemanusiaan
Secara historis dan teologis, Ramadhan memiliki posisi istimewa dalam Islam. Al-Qur’an diturunkan pada bulan ini, sebagaimana ditegaskan dalam ajaran Islam, dan puasa diwajibkan sebagai sarana membentuk ketakwaan. Secara tegas, Allah SWT dalam QS al-Baqarah: 183 menyatakan: “Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa”.
Namun di balik itu, Ramadhan membangun narasi kemanusiaan yang mendalam. Lapar dan dahaga bukan sekadar latihan fisik, melainkan pengalaman empatik. Dalam humaniora, pengalaman adalah pintu masuk untuk memahami makna. Ketika seseorang menahan lapar, ia bukan hanya mengendalikan diri, tetapi juga belajar memahami realitas orang-orang yang hidup dalam kekurangan. Di sini, puasa menjadi pendidikan etika sosial—ia membentuk sensitivitas, bukan hanya kesalehan pribadi.
Baginda Rasulullah Saw. pernah mengingatkan “Berapa banyak orang yang berpuasa, tidak mendapat pahala puasa kecuali hanya lapar dan hausnya saja. Berapa banyak orang yang bangun malam, tidak mendapat pahala kecuali hanya bangun malamnya saja.” Ini artinya, sejatinya lapar dan haus bukan parameter yang hakiki bagi orang yang berpuasa. Tetapi berpuasa itu melibatkan kondisi jiwa dan penataan emosi atau nafsu. Berpuasa sejatinya bukan menghindari hal-hal yang membatalkan secara fisik tetapi jiwanya juga harus dijaga dan dihindarkan dari hal-hal yang dapat mengotori keagungan puasa.
Ramadhan juga membangun narasi kolektif. Dari sahur hingga berbuka, dari masjid hingga ruang keluarga, masyarakat merayakan kebersamaan. Tradisi buka bersama, berbagi takjil, dan tarawih berjamaah menunjukkan bahwa Ramadhan adalah peristiwa sosial yang memperkuat kohesi komunitas. Seolah mengingatkan kita bahwa manusia pada hakikatnya adalah zoon politicon. Yakni, manusia adalah makhluk yang tidak bisa lepas dari bermasyarakat, hidup bersama yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lain.
Dari Kronologi ke Kairos
Humaniora mengajarkan bahwa waktu bukan hanya kronologi (chronos), tetapi juga momen bermakna (kairos). Ramadhan mengubah persepsi waktu manusia. Siang menjadi ruang penahanan diri, malam menjadi ruang kontemplasi. Kalender Hijriyah tidak hanya menandai pergantian bulan, tetapi menghadirkan kesadaran spiritual tentang siklus kehidupan.
Dalam tradisi Islam, sepuluh malam terakhir memiliki nilai istimewa karena diyakini terdapat Lailatul Qadar—malam yang lebih baik dari seribu bulan. Keyakinan ini mengajarkan bahwa kualitas waktu lebih penting daripada kuantitasnya. Dalam bahasa humaniora, Ramadhan mendidik manusia untuk menghargai intensitas makna, bukan sekadar durasi hidup.
Imam Ibnu Rajab mengingatkan, bahwa Ramadhan adalah momen untuk memanen hasil (syahr al-zar’). Ramadhan menjadi puncak produktifitas amal ibadah kebaikan, setelah dua bulan sebelumnya seseorang memulai dan membiasakan amal ibadah kebaikan. Saat bulan Rajab menjadi awal komitmen menabur benih kabikan dan bulan Sya’ban menjadi saat-saat menjaga dan memupuk kebaikan yang telah dikomitmenkan dalam diri.
Maka, Ramadhan tidak sekedar menjadi ruang dan waktu yang hadir dan lalu digantikan dengan bulan berikutnya. Tetapi, menjadi momen paling mulia yang bermakna bagi umat Islam khususnya, dimana di dalamnya persepsi pikiran seseorang ditujukan pada “penyambutan” Tamu Allah yang berupa bulan Ramadhan yang hadir dengan membawa Samudra rahmat, ampunan (maghfirah), dan pembebasan dari api neraka (itq min al-nar).
Membangun Etika Solidaritas
Salah satu inti Ramadhan adalah zakat dan sedekah. Praktik ini bukan sekadar distribusi materi, tetapi pernyataan moral bahwa kekayaan memiliki dimensi sosial. Dalam kajian humaniora, solidaritas adalah fondasi peradaban. Masyarakat yang kuat bukan yang paling kaya, tetapi yang paling peduli.
Dalam hal zakat, al-Qur’an menggunakan bahasa yang unik saat menegaskan perintah untuk mengeluarkan sedakah. Dalam surat al-Taubah ayat 103 difirmankan: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka.” Perintah zakat hadir dalam bentuk kata “ambillah” (khudz) seolah-olah ada pemaksaan, bukan dalam bentuk misalnya “keluarkanlah zakat kalian”. Imam Fakhruddin ar-Razi dalam tafsirnya Mafatih al-Ghaib menjelaskan, perintah zakat ini menjelaskan bahwa dalam pengabdian kepada Allah menampakkan tobat dan penyesalan saja tidak cukup, dan manusia cenderung lebih mencintai hartanya serta enggan untuk menginfakkannya. Maka, menurutnya kebenaran tobat dan penyesalan baru akan nyata jika sudah mengeluarkan zakat yang wajib dan tidak merasa berat dalam menunaikannya.
Di tengah krisis global—ketimpangan ekonomi, konflik kemanusiaan, dan disrupsi teknologi—nilai solidaritas Ramadhan menjadi semakin relevan. Ia menegaskan bahwa manusia tidak dapat hidup sebagai individu terisolasi. Puasa melatih kesadaran akan keterhubungan (interconnectedness). Dalam konteks ini, Ramadhan adalah kritik terhadap individualisme ekstrem dan konsumerisme yang mereduksi manusia menjadi sekadar makhluk ekonomi.
Puasa menjadi pengalaman batin seseorang dimana saat menjalani puasa ia merasakan kondisi dirinya di titik nadir (seperti harus menahan lapar, haus dan hal-hal yang dapat membatalkan puasa); momen merasakan kondisi jiwa dan raga berada dalam titik kelemahan dan kekurangan, mengendalikan keinginan dan nafsu dari segala syahwat yang diinginkan.
Ramadhan betul-betul menjadi momen pembentukan diri kemanusiaan (human formation). Bukan sekadar ajang gagah-gagahan dalam menahan lapar dan haus dahaga. Dalam puasa terdapat relasi langsung antara orang yang puasa (sho’im) dengan Allah SWT. “Puasa adalah untuk-Ku, dan Aku sendiri yang akan memberikan ganjaran (balasan) padanya,” begitulah dinyatakan dalam sebuah hadis Qudsi. Juga di dalamnya ada dimensi etis-sosial, yakni membangun sifat kejujuran, sabar dan solidaritas kemanusiaan.
Dalam bahasa humaniora, Ramadhan adalah proses humanisasi. Ia mengembalikan manusia pada fitrahnya: makhluk yang sadar akan keterbatasan, namun memiliki kapasitas untuk mencintai, berbagi, dan memaknai hidup.
Membaca Ramadhan melalui humaniora berarti melihat ibadah sebagai pengalaman makna. Puasa bukan sekadar menahan diri dari makan dan minum, tetapi menahan diri dari kekerasan, keserakahan, dan egoisme. Ia adalah latihan untuk menjadi manusia yang lebih utuh.
Di tengah dunia yang sering kehilangan arah, Ramadhan menawarkan jeda. Ia mengajak manusia berhenti sejenak, menata ulang orientasi hidup, dan mengingat kembali bahwa kemuliaan tidak terletak pada kekuasaan atau kepemilikan, tetapi pada kualitas kemanusiaan. Selamat menjalani Ramadhan! [mff-Infopub]