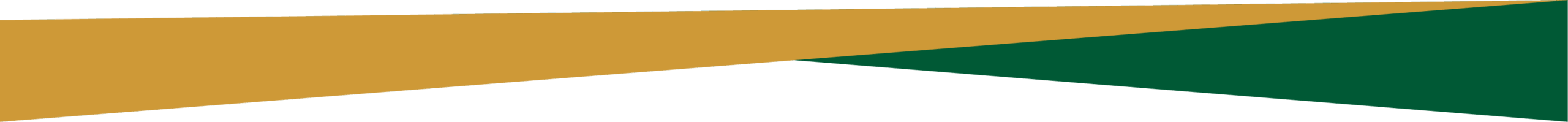HUMANIORA – (6/1/2025) Perkembangan kecerdasan buatan ( Artificial Intelligence /AI) telah menjadi salah satu penanda paling kuat dari perubahan zaman. Mesin kini tidak hanya membantu manusia menghitung dan menyimpan data, tetapi juga mampu menulis teks, menerjemahkan bahasa, menganalisis wacana, bahkan menciptakan karya seni. Di tengah euforia efisiensi dan kecepatan ini, muncul pertanyaan yang kerap berulang di ruang-ruang akademik dan publik: masih relevankah ilmu humaniora di era ketika mesin tampak mampu “berpikir” seperti manusia?
Pertanyaan tersebut tidak sekadar teknis, melainkan filosofis. Ia mencerminkan kecemasan kolektif tentang posisi manusia di tengah dominasi teknologi. Namun, justru pada titik inilah ilmu humaniora menemukan kembali relevansi dan urgensinya. Alih-alih tersingkir, humaniora hadir sebagai jangkar nilai yang memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak kehilangan arah kemanusiaannya.
Kemajuan Teknologi dan Ilusi Netralitas
AI sering dipresentasikan sebagai teknologi yang objektif, netral, dan bebas nilai. Algoritma bekerja berdasarkan data, statistik, dan pola matematis. Namun, anggapan ini problematis. Setiap teknologi lahir dari keputusan manusia—tentang data apa yang digunakan, nilai apa yang diutamakan, serta kepentingan siapa yang dilayani. Dengan kata lain, teknologi tidak pernah benar-benar netral.
Di sinilah humaniora memainkan peran krusial. Filsafat, misalnya, membantu kita mempertanyakan dimensi etika dari pemanfaatan AI: siapa yang bertanggung jawab ketika algoritma bias? Sastra dan kajian budaya menyingkap bagaimana teknologi membentuk—dan dibentuk oleh—narasi sosial. Sejarah mengingatkan bahwa setiap revolusi teknologi selalu membawa konsekuensi sosial yang kompleks, sering kali tidak merata. Tanpa perspektif humaniora, kita berisiko menerima teknologi secara taken for granted, tanpa refleksi kritis.
Humaniora dan Pemahaman tentang Manusia
Jika ilmu eksakta bertanya bagaimana sesuatu bekerja, maka humaniora bertanya mengapa hal itu bermakna bagi manusia. Perbedaan ini bukanlah sekadar pembagian akademik, melainkan perbedaan cara pandang terhadap dunia. AI mungkin mampu mengolah bahasa, tetapi ia tidak mengalami bahasa sebagai pengalaman hidup. Ia dapat meniru emosi dalam teks, tetapi tidak merasakan luka, harapan, atau kegelisahan manusia.
Kajian sastra mengajarkan empati—kemampuan untuk memahami pengalaman orang lain melalui cerita. Filsafat melatih keberanian berpikir kritis dan mempertanyakan asumsi yang mapan. Studi bahasa membantu kita memahami bagaimana makna dibangun, dinegosiasikan, dan diperdebatkan dalam konteks sosial dan budaya tertentu. Semua ini adalah keterampilan yang tidak dapat direduksi menjadi baris kode.
Di tengah dunia yang semakin terotomatisasi, justru kualitas-kualitas inilah yang paling dibutuhkan: kemampuan menafsirkan, menimbang, dan mengambil keputusan secara bijaksana.
Bahasa, Budaya, dan Risiko Reduksi Makna
AI menunjukkan performa luar biasa dalam pemrosesan bahasa. Namun, bahasa bukan sekadar sistem tanda yang bisa dipetakan secara statistik. Ia adalah cermin budaya, sejarah, dan relasi kekuasaan. Sebuah kata dapat membawa makna yang berbeda tergantung konteks sosial, latar budaya, dan pengalaman kolektif suatu masyarakat.
Tanpa pemahaman humaniora, teknologi bahasa berisiko mereduksi kompleksitas tersebut. Terjemahan yang “benar secara gramatikal” bisa jadi keliru secara kultural. Narasi yang tampak netral bisa menyimpan bias ideologis. Di sinilah kajian bahasa, sastra, dan budaya menjadi penyangga agar teknologi tidak menghapus keragaman makna dan identitas.
Pengembangan AI yang bertanggung jawab tidak cukup hanya melibatkan insinyur dan ilmuwan data. Ia membutuhkan dialog lintas disiplin—antara teknologi dan humaniora—agar inovasi tidak tercerabut dari nilai-nilai kemanusiaan.
Humaniora di Ruang Akademik dan Sosial
Di lingkungan perguruan tinggi, ilmu humaniora sering dipersepsikan sebagai bidang yang “tidak praktis” atau “kurang menjanjikan secara ekonomi”. Pandangan ini sempit dan tidak sejalan dengan realitas kebutuhan masyarakat kontemporer. Dunia kerja saat ini tidak hanya membutuhkan individu yang menguasai teknologi, tetapi juga mereka yang mampu berpikir kritis, berkomunikasi efektif, memahami konteks sosial, dan bekerja lintas budaya.
Lulusan humaniora memiliki keunggulan dalam membaca wacana, menganalisis fenomena sosial, dan merumuskan gagasan secara argumentatif. Keterampilan ini relevan di berbagai sektor: pendidikan, media, diplomasi, kebijakan publik, industri kreatif, hingga pengembangan konten digital berbasis AI. Humaniora tidak berdiri berlawanan dengan teknologi, melainkan melengkapinya.
Mahasiswa Humaniora dan Tantangan Masa Depan
Bagi mahasiswa humaniora, kehadiran AI seharusnya dipahami bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai tantangan intelektual dan peluang kolaborasi. Dengan bekal kepekaan sosial dan kemampuan reflektif, mahasiswa humaniora dapat berperan sebagai jembatan antara teknologi dan masyarakat.
Mereka dapat mengkritisi narasi tentang “kemajuan” yang semata-mata diukur dari kecepatan dan efisiensi. Mereka dapat menyuarakan pertanyaan tentang keadilan, inklusivitas, dan dampak sosial dari otomatisasi. Di tengah banjir informasi dan konten yang dihasilkan mesin, kemampuan membaca secara kritis dan menulis dengan kesadaran etis menjadi semakin bernilai.
Humaniora sebagai Penjaga Arah Peradaban
Pada akhirnya, pertanyaan tentang relevansi humaniora di era AI bukanlah pertanyaan tentang masa lalu versus masa depan. Ia adalah pertanyaan tentang arah peradaban. Teknologi dapat memperluas kemampuan manusia, tetapi tidak dapat menggantikan kebijaksanaan manusia dalam menentukan tujuan.
Ilmu humaniora hadir untuk mengingatkan bahwa kemajuan sejati bukan hanya soal apa yang bisa kita lakukan, tetapi juga tentang apa yang seharusnya kita lakukan. Di tengah kecanggihan mesin, humaniora menjaga nilai, makna, dan martabat manusia agar tidak larut dalam logika efisiensi semata.
Di era AI, ilmu humaniora bukanlah sisa dari masa lalu, melainkan fondasi bagi masa depan yang beradab. Sebab ketika mesin menjadi semakin cerdas, manusia justru dituntut untuk menjadi semakin bijaksana.
[Asf/Infopub]